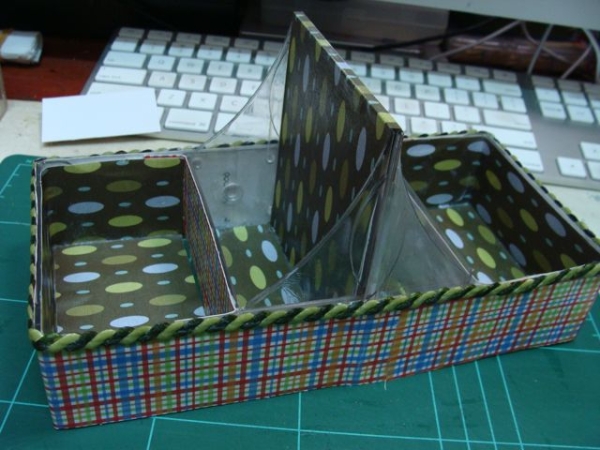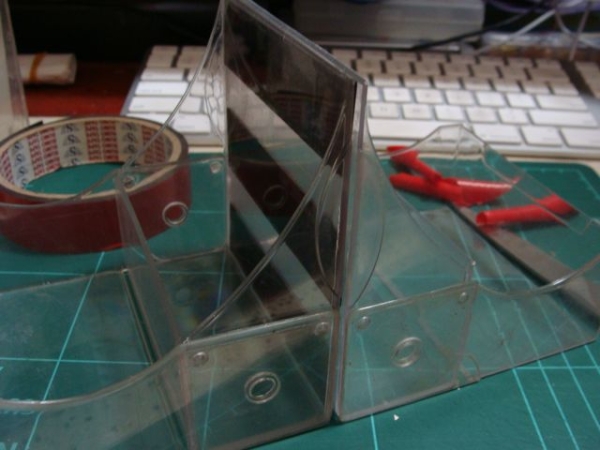ADA beberapa hal, yang
menarik untuk dicermati dengan “hadirnya” Lady Gaga di Indonesia, yaitu: pertama,
bahwa Indonesia telah masuk dalam garis internasional untuk mempopulerkan
musik, baik dalam kebutuhan promosi musisi lokal yang go international, atau
pun menerima kedatangan promosi musik dari luar. Tentunya, hal ini akan semakin
memperluas jaringan kerja musisi di Indonesia, memajukan industri musik,
termasuk di dalamnya adalah terdapat kepentingan diplomasi antarnegara. Hal kedua,
akan selalu terdapat perbedaan dalam kemasan musik dan performance dari
setiap musisi dan artis, yang sebetulnya memberikan celah bagi musisi lain,
untuk dapat memberikan tampilan berbeda, sehingga tidak saja persoalan
kualitas, kreativitas, tentu saja akan terkait dengan hal ekonomisasi dalam
bidang musik. Perkara ekonomi, walaupun bukan elemen utama dalam berkarya dan
mencipta musik, tidak dapat terpisahkan. Popularitas seseorang tentunya akan
memberikan kesempatan bagi orang lain, untuk dapat dijadikan sebagai tolok ukur
atas kualitas musik, secara terseleksi para penggemar akan terbentuk dengan
sendirinya. Kepentingan industri musik, memang tidak dapat dipisahkan dari
sistem-sistem yang sudah mapan dan berjalan, sehingga ketika terjadinya suatu
benturan, merupakan hal yang wajar, selama benturan ini tidak bersifat
pemaksaan. Sistem budaya Indonesia, bahkan pada setiap daerah, adat istiadat,
agama dan kepercayaan, ataupun suatu negara lain, ketika bertemu pada satu
lokasi, tidak dapat dipungkiri akan terjadi “perdebatan”. Menjaga eksistensi
dan idealisme bagi seorang musisi, terkadang harus dikompromikan dengan
sistem-sistem yang sebetulnya bukan memaksa untuk memperbarui, tetapi bagaimana
antara sistem ini dengan idealisme musisi dapat bersinergi dengan baik.
Hal ketiga, persoalan moral dan etika, tidak dapat dengan sendirinya
dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan terdiri dari berbagai macam
persoalan, setidaknya termasuk di dalamnya adalah budaya, latar belakang
pendidikan dan kepentingan, gejala sosial dan politik tertentu, bahkan terkait
pula dengan kepentingan ekonomi. Lady Gaga, bukanlah satu-satunya “sumber”
kerusuhan moral dan etika, jika nantinya dilihat sebagai dampak atas terjadinya
komplikasi pada persoalan sosial, budaya, dan agama di wilayah Indonesia. Penampilan
seronok ala Lady Gaga, adalah salah satu dari sekian banyak sumber persoalan
yang muncul pada komunitas sosial masyarakat, dan tidak dapat dikatakan sebagai
bahan tambahan untuk memperparah. Tentu tidaklah patut, jika kemudian
keseronokan ala Lady Gaga, dipertautkan dengan seronoknya tampilan beberapa
musisi Indonesia. Latar belakang pembentuk gaya masing-masing musisi, memiliki
sumber referensi yang berbeda. Jika memang suatu sistem (baik itu budaya, kode
etik sosial, dan agama) memandang Lady Gaga memiliki keseronokan yang luar
biasa, seharusnya sistem ini berkerja secara menyeluruh dalam melakukan
penyaringan dan sensor terhadap musisi-musisi lainnya. Terlepas keberpihakan
atau tidak media massa di dalam proses sensor ini, masyarakat harus kritis dan
pintar dalam mengendalikan setiap hiburan yang disajikan oleh media. Termasuk
untuk mengkritisi tayangan-tayangan yang mengarah dan berkaitan pada dampak
sosial, moral, serta etika.
Kepanikan-kepanikan yang dibicarakan oleh Yasraf Amir Piliang pada pengantar Dunia
yang Berlari: Mencari Tuhan-tuhan Digital, merupakan realita yang terjadi
pada masyarakat sosial di Indonesia. Misalnya, kepanikan konsumsi, ketika
perilaku mengkonsumsi ini berlaku secara berlebihan dan tidak diketahui
fungsinya. Atau panik tontonan, ketika manusia mempertontonkan apa saja tanpa
ada spiritnya. Demikian juga, ketika terjadi kepanikan seksualitas yang
mengekspos setiap bagian tubuh yang tidak diiringi oleh makna-makna.
Kepentingan media dan kelompok masyarakat tertentu atas tubuh Lady Gaga, adalah
bagian dari kepanikan dari sekian banyak kepanikan yang terjadi dalam
masyarakat. Tubuh Lady Gaga merupakan penanda atas terjadinya beberapa reaksi
dan gejolak sosial pada masyarakat Indonesia. Kekhawatiran pada dampak yang
diakibatkan karena popularitas tubuh Lady Gaga terlalu berlebihan. Justru, hal
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemampuan masyarakat untuk mengatur
dan mengelola perilaku mengkonsumsi secara tepat. Tidak terkecuali atas
pilihan-pilihan yang disajikan baik oleh media penyedia jasa hiburan, media
massa, atau pun kelompok-kelompok lain yang berujung pada benturan budaya
lokal. Spirit tontonan dan perilaku menonton dengan benar adalah persoalan yang
tidak dengan sendirinya terbentuk, tanpa adanya motivasi, melainkan saling
berhubungan dengan kemapanan budaya, atau bahkan kemapanan dalam hal moral dan
etika penonton itu sendiri.
Tidak dapat juga disalahkan, ketika ada arus keras yang menentang kedatangan
Lady Gaga di Indonesia, apalagi saat dipertautkan dengan satu sistem yang
memiliki landasan pikir tertentu, dan bertolak belakang dengan gaya tampilan
Lady Gaga. Demikian pula sebaliknya, bahwa sistem ini tidak dapat memaksa orang
lain untuk mengikuti pola pikirnya. Ketika kedua landasan pikir berbeda dan
tetap bertahan pada idealisme masing-masing, maka jalan sebaiknya yang ditempuh
bukan pada tawar menawar idealisme. Karena pada saat terjadi musyawarah untuk
mencapai mufakat pada idealisme, yang terjadi adalah saling memaksakan
kepentingan.
Kerumitan sosial yang muncul tentang Lady Gaga adalah ketika terjadinya usaha
penyensoran oleh beberapa kelompok, dengan dasar keyakinan tertentu. Seperti
dibahas oleh Marshall A. Clark untuk pengantar dalam Budaya Populer sebagai
Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer, bahwa
usaha penyensoran tontonan di Indonesia (tidak terkecuali gaya Lady Gaga) lebih
kuat dorongannya yang bersumber dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
Disebutkan oleh Clark, kebebasan berekspresi tidak akan mampu diselamatkan oleh
pasar, karena ditakutkan mengundang kelompok religius radikal untuk mengamuk,
dan berdampak pada sisi ekonomi. Digambarkan, tidak akan ada perusahaan sinema
(hiburan) yang mau mengambil reksiko diamuk massa akibat penampilan seorang
artis atau pun musisi tertentu, tidak terkecuali Lady Gaga. Jelas sekali, bahwa
kelompok-kelompok penekan ditingkat lokal (memanfaatkan sentimen keagamaan)
terlihat jauh lebih kuat daripada aparat dan lembaga resmi negara, termasuk
mementahkan peran Undang-Undang tentang Pornografi. Sepertinya, tarik ulur dan
penyensoran konser Lady Gaga di Indonesia, lebih cenderung pada politisasi
kepentingan kelompok-kelompok. Seharusnya, usaha penyensoran ini berlaku pada
penampilan-penampilan musisi lain, termasuk menyeluruh pada setiap bagian (isi
dan makna) yang disajikan pada masyarakat.